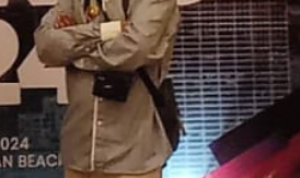Di Balik Lelucon Sehari-hari: Microaggression sebagai Senjata Politik Halus
Oleh: Muhamad Alfarozy
Mahasiswa Program Studi Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Microaggression: Candaan Ringan, Dampak Nyata
Di sebuah kantor di Jakarta Selatan, terjadi sebuah peristiwa yang sekilas tampak sepele, tetapi meninggalkan ketidaknyamanan yang nyata. Ketika sebuah donat JCO dibeli, sebuah komentar muncul seakan-akan pengenalannya tidak diketahui oleh pihak yang dianggap berasal dari kampung. Candaan ringan seperti ini termasuk microaggression, yaitu ejekan halus yang merendahkan identitas tertentu melalui kata-kata atau tindakan sehari-hari. Konsep microaggression pertama kali diperkenalkan oleh psikiater Chester M. Pierce pada tahun 1970-an dan kemudian dikembangkan oleh Derald Wing Sue. Microaggression terjadi dalam bentuk komentar, perilaku, atau sikap yang tampak biasa, tetapi menyimpan pesan negatif terhadap ras, gender, kelas sosial, agama, budaya, atau asal daerah. Efek dari microaggression bersifat kumulatif dan psikologis, menyebabkan perasaan terpinggirkan, rendah diri, dan kebingungan emosional dalam menghadapi interaksi sosial yang seolah ringan namun merendahkan. Dampaknya tidak terlihat secara langsung, tetapi perlahan membentuk batasan sosial dan persepsi yang menempatkan beberapa pihak pada posisi inferior.
Dimensi Politik Microaggression
Fenomena microaggression tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga memiliki dimensi politik yang penting. Hal ini merupakan manifestasi dari politik identitas, di mana kelompok yang dianggap pusat menegaskan dominasi sosial terhadap kelompok yang dianggap periferi. Stereotip yang melekat pada asal daerah atau status sosial sering kali dijadikan bahan candaan, dan candaan itu, meskipun tampak ringan, menegaskan struktur hierarki sosial yang ada. Teori symbolic power dari Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa bahasa merupakan alat kekuasaan. Kata-kata sehari-hari dapat digunakan untuk menegaskan posisi sosial tertentu, memperkuat dominasi kelompok tertentu, dan menyingkirkan kelompok lain dari pusat perhatian sosial dan budaya. Candaan yang menyiratkan inferioritas pihak lain sebenarnya merupakan bentuk kekuasaan simbolik yang halus, tetapi efektif dalam mempertahankan hierarki yang ada.
Microaggression dan Politik Kelas
Selain politik identitas, microaggression juga berkaitan erat dengan politik kelas. Istilah seperti “kampungan”, “norak”, atau “tidak modern” menjadi cara untuk menegaskan superioritas sosial dan ekonomi, sementara menyingkirkan kelompok yang dianggap kurang berdaya dari pusat budaya dan sosial. Dalam konteks ruang kerja atau institusi pendidikan, bentuk-bentuk halus ini dapat membatasi representasi sosial dan kesempatan berpartisipasi dalam ranah publik. Dampak kumulatifnya tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga politis. Struktur sosial yang tersusun melalui microaggression membuat sebagian pihak merasa tidak pantas muncul di ruang publik, menahan partisipasi, dan membatasi pengakuan terhadap keberagaman budaya. Perilaku halus ini sering kali diabaikan atau dianggap lelucon biasa, padahal secara simbolik memperkuat ketimpangan sosial yang ada.
Ketimpangan Sosial Kota dan Daerah
Fenomena microaggression sering muncul sebagai manifestasi ketimpangan sosial antara kota dan daerah. Individu yang berasal dari kampung atau daerah kerap dianggap kurang modern, kampungan, atau tidak mengetahui hal-hal yang lazim di perkotaan, seperti produk populer atau tren budaya kota. Candaan atau komentar halus seperti ini, meskipun tampak ringan, sesungguhnya menegaskan hierarki sosial tersirat, di mana kelompok perkotaan secara simbolik menempatkan diri sebagai lebih unggul. Ketimpangan ini muncul dari perbedaan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan informasi antara kota dan daerah. Ketika interaksi sehari-hari mengandung asumsi bahwa warga dari daerah kurang memahami hal-hal “umum” di kota, microaggression bekerja untuk mempertahankan dominasi sosial dan menguatkan stereotip yang merugikan. Akumulasi perilaku ini menimbulkan ketidakamanan psikologis, rasa rendah diri, dan pembatasan partisipasi sosial atau profesional, sekaligus memperkuat persepsi bahwa ruang perkotaan hanya milik mereka yang dianggap normatif. Dengan kata lain, bahasa, lelucon, dan candaan sehari-hari menjadi alat kekuasaan simbolik yang menegaskan ketimpangan sosial dan meminggirkan kelompok dari daerah secara halus namun nyata.
Bahasa Sebagai Alat Kekuasaan
Bahasa yang digunakan sehari-hari memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi dan norma sosial. Microaggression menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui hukum atau kebijakan formal, tetapi juga melalui interaksi sosial yang tampak biasa. Setiap kata dan candaan dapat menjadi medium untuk menegaskan siapa yang dianggap layak dan siapa yang dianggap tidak pantas. Hal ini membuktikan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen politik yang halus dan tersembunyi. Struktur sosial, norma budaya, dan ketimpangan kelas diperkuat melalui cara ini, meskipun tanpa disadari oleh pelaku. Interaksi sehari-hari yang terus-menerus menyiratkan inferioritas dapat menimbulkan efek psikologis yang bertahan lama, membatasi keberanian untuk tampil, serta memengaruhi kepercayaan diri dalam ranah sosial maupun profesional.
Dampak Jangka Panjang Microaggression
Efek dari microaggression tidak bersifat sementara. Dalam skala lebih luas, microaggression berkontribusi pada ketimpangan representasi dalam institusi publik dan organisasi. Pihak yang sering menjadi target mungkin mengurangi keterlibatan atau bahkan menarik diri dari forum publik, sehingga dominasi kelompok lain semakin terlihat dan diperkuat. Akumulasi komentar dan perilaku halus ini secara tidak langsung membentuk norma sosial yang memisahkan pusat dari pinggiran, dan memperkuat stereotip lama yang melekat pada asal-usul, kelas sosial, atau latar belakang budaya tertentu.
Kesadaran dan Solusi
Kesadaran terhadap fenomena ini menjadi penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif. Menghormati pihak lain bukan bergantung pada status sosial, kota asal, atau kemampuan ekonomi, tetapi pada kesadaran, empati, dan keberanian untuk menantang hierarki halus yang tersirat dalam interaksi sehari-hari. Microaggression merupakan pengingat bahwa dominasi dapat muncul dalam bentuk yang paling halus sekalipun, dan perubahan hanya mungkin terjadi dengan kesadaran kolektif terhadap pola-pola bahasa, candaan, dan sikap yang memperkuat ketidaksetaraan sosial. Pendidikan, pelatihan keberagaman, dan refleksi diri terhadap pola komunikasi sehari-hari menjadi kunci untuk mengurangi pengaruh microaggression. Setiap interaksi memiliki potensi untuk menegaskan atau menantang struktur sosial yang ada. Kesadaran akan hal ini memungkinkan terciptanya ruang sosial yang lebih egaliter, di mana perbedaan bukan sumber hinaan, tetapi dihargai sebagai bagian dari keragaman budaya dan sosial. Microaggression, meskipun halus, adalah bentuk kekuasaan yang nyata, dan hanya dengan pemahaman serta tindakan sadar, kekuasaan simbolik yang tersirat dapat diubah menjadi interaksi yang setara dan inklusif.