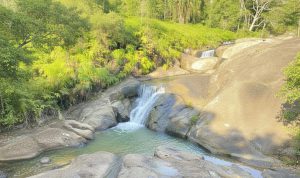Perempuan di Panggung Rabab Pasisia: Antara Tradisi dan Tantangan Sosial
Oleh: Annisa Putri
Kemunculan perempuan sebagai pendendang dalam pertunjukan Rabab Pasisia merupakan babak baru dalam sejarah seni Minangkabau. Jika dahulu panggung rabab hanya diisi oleh laki-laki yang bersuara berat dan berwibawa, kini suara perempuan hadir, lembut, penuh perasaan, namun tidak kalah kuat. Suara mereka menjadi gema baru yang menembus batas tradisi, membawa kesegaran pada seni yang telah berusia ratusan tahun.
Seni Rabab Pasisia sendiri bukan hanya hiburan. Ia adalah seni tutur, bentuk komunikasi sosial yang memadukan kisah (kaba) dengan iringan alat musik rabab, sebuah biola tradisional berdawai dua yang menghasilkan suara serak tapi menyentuh. Tradisi ini tumbuh di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat, tempat masyarakat hidup berdampingan dengan laut, gelombang, dan penderitaan panjang akibat kolonialisme. Dalam kesunyian malam, di bawah cahaya pelita, seniman rabab menuturkan kisah cinta, pengkhianatan, perjuangan, dan nasihat hidup.
Namun selama berabad-abad, suara itu hanya milik kaum laki-laki. Adat memandang ruang publik sebagai milik mereka, sementara perempuan diharapkan menjaga kehormatan di dalam rumah. Hartitom, peneliti seni dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, mencatat bahwa pada masa lalu, “perempuan dianggap tidak layak tampil di panggung karena bertentangan dengan norma kesopanan.” Bahkan, sekadar hadir di tempat hiburan malam pun bisa menimbulkan stigma sosial.
Perubahan mulai terasa ketika realitas sosial ekonomi ikut bergeser. Pasca tahun 1980-an, kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang sulit mendorong banyak keluarga untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Dalam situasi itu, Rabab Pasisia menjadi salah satu sarana ekonomi baru dan perempuan mulai mengambil bagian. Mereka tidak lagi hanya penonton, tetapi ikut menghidupkan panggung sebagai pendendang.
Hartitom mencatat bahwa pendendang perempuan membawa perubahan signifikan: mereka memperkaya suasana pertunjukan dengan emosi dan kelembutan yang tidak dimiliki penyanyi laki-laki. Lagu-lagu Sikambang yang dulu bernada heroik kini bisa terdengar lebih lirih, penuh rasa haru, seolah menyuarakan kerinduan dan kesetiaan. Perempuan juga membawa sudut pandang baru dalam narasi kaba, tentang ibu yang menunggu anaknya merantau, atau istri yang ditinggal pergi oleh suaminya ke rantau jauh. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh sisi humanitas yang dalam.
Namun, langkah perempuan menuju panggung tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Masih banyak kalangan adat dan agama yang menganggap bahwa perempuan pendendang menyalahi batas sopan santun. Tampil di depan khalayak laki-laki, apalagi hingga larut malam, dianggap “tidak pantas” bagi perempuan Minang. Beberapa pendendang bahkan menerima cibiran, dianggap “murahan” atau “melanggar adat”. Di sinilah letak ironi, masyarakat yang mengagungkan sistem matrilineal, di mana perempuan menjadi pewaris suku dan rumah gadang, justru membatasi ruang ekspresinya di ranah publik.
Meski demikian, generasi pendendang perempuan tidak menyerah. Mereka menegosiasikan posisi mereka di antara dua dunia, dunia adat yang ketat dan dunia modern yang menuntut kebebasan berekspresi. Mereka tetap mengenakan pakaian sopan, menjaga perilaku, dan menekankan bahwa seni tidak identik dengan pelanggaran moral. Di atas panggung, mereka menampilkan kekuatan baru, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan budaya dan emosi.
Seiring waktu, publik mulai menerima kehadiran mereka. Banyak pendendang perempuan seperti Mel Rasani atau Upiak Malai yang kini dihormati bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai penjaga tradisi. Mereka membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri di panggung adat tanpa kehilangan kehormatan. Bahkan, dalam beberapa pertunjukan modern, perempuan justru menjadi daya tarik utama karena mampu membawakan kisah dengan kelembutan dan penghayatan yang menyentuh hati penonton.
Fenomena ini memperlihatkan pergeseran makna seni dalam masyarakat Minangkabau. Dulu, Rabab Pasisia hanya menjadi milik laki-laki yang bercerita tentang perang dan keberanian. Kini, ia menjadi ruang dialog antara laki-laki dan perempuan, antara tradisi dan modernitas, antara suara lama dan suara baru. Munculnya perempuan di panggung tidak berarti pengkhianatan terhadap adat, tetapi justru memperkaya ekspresi budaya Minangkabau.
Lebih dari itu, perempuan pendendang telah mengembalikan fungsi asli seni sebagai ruang untuk menyuarakan kemanusiaan. Di tangan mereka, Rabab Pasisia bukan hanya tempat menceritakan kisah duka, tetapi juga tempat merayakan harapan. Melalui nyanyian Sikambang, mereka menyuarakan kegigihan, kesabaran, dan cinta terhadap budaya yang telah membesarkan mereka.
Kini, ketika dunia digital memberi ruang baru bagi seni tradisi, banyak pendendang perempuan mulai tampil melalui media daring. Pertunjukan Rabab Pasisia direkam, diunggah ke YouTube, dan ditonton ribuan orang, dari Padang hingga Malaysia. Tradisi yang dulu hidup di surau kini menemukan panggung baru di layar-layar modern.
Munculnya perempuan di panggung Rabab Pasisia adalah bukti bahwa adat Minangkabau bukan sistem yang kaku, melainkan budaya yang hidup dan mampu menyesuaikan diri. Di tengah kritik dan keterbatasan, mereka menegaskan satu hal penting, bahwa menjaga kehormatan tidak berarti membungkam suara. Dan dalam setiap gesekan rabab yang mengiringi suara mereka, terselip pesan abadi dari ranah Minang, bahwa seni, seperti kehidupan, selalu tumbuh di antara batas dan keberanian.