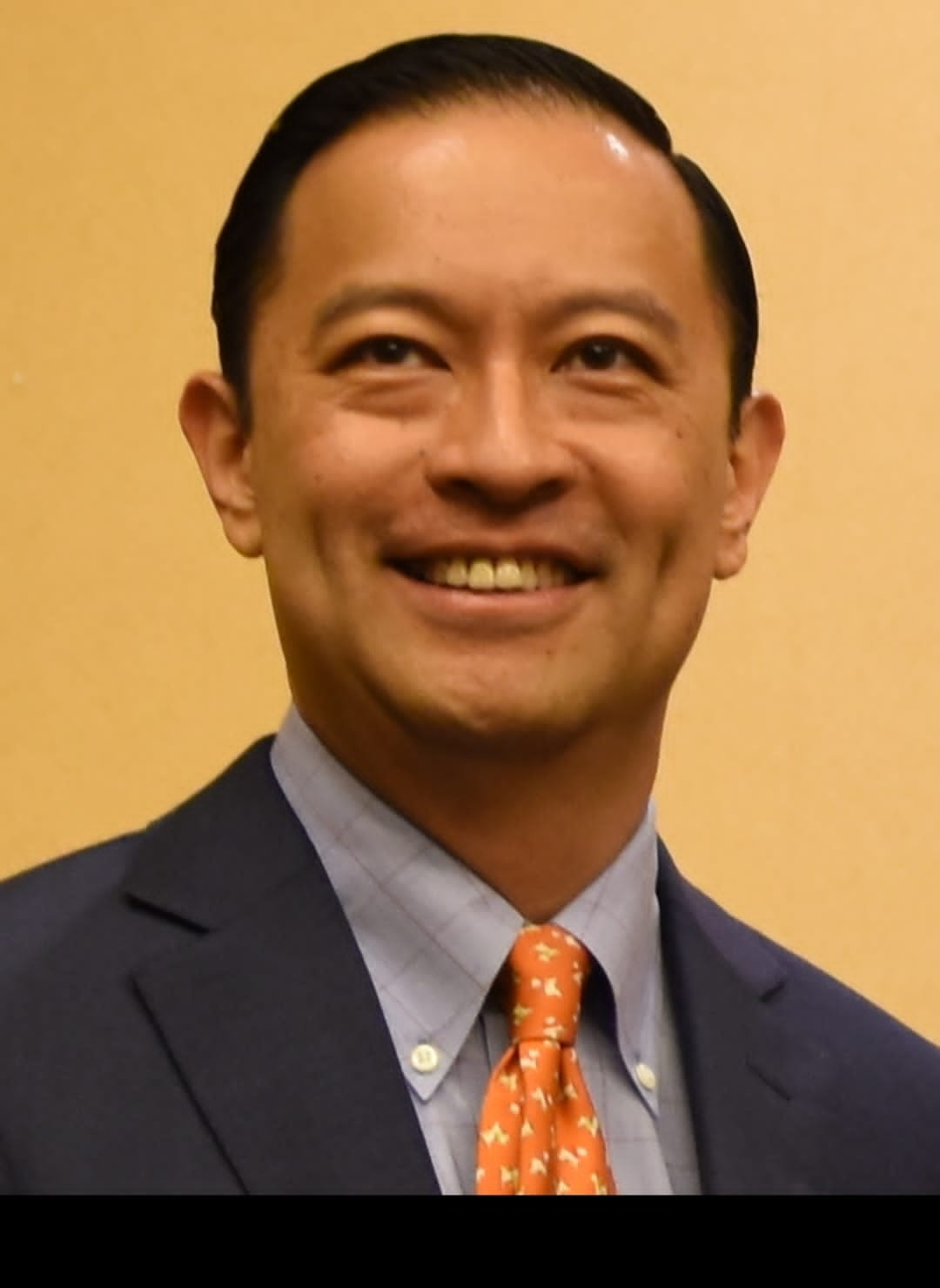Membaca Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto: Wajah Ganda Keadilan Indonesia
Oleh: Ardinal Bandaro Putiah
Ketua III Pemuda Muslimin Indonesia
Ketika Keadilan Dikorbankan di Meja Kekuasaan
Indonesia, negeri yang lahir dari rahim perjuangan dan jerit rakyat, kembali menyaksikan sebuah pertunjukan hukum yang membuat kepala rakyat kecil menggeleng dan hati mereka semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dua nama mencuat dari istana, Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto. Keduanya bukan tokoh biasa. Mereka elite. Mereka punya akses kekuasaan. Dan yang lebih penting mereka mendapat pengampunan negara.
Satu dengan abolisi, yang lain dengan amnesti. Dalam waktu bersamaan, pada hari yang nyaris seremonial. Maka gegap gempita pujian pun muncul dari lingkaran dalam kekuasaan, sementara di luar sana, di perkampungan miskin, di kantor pengadilan negeri kecil, di jeruji para terdakwa kasus petty crime terdengar gumaman getir “Mengapa bukan kami?”
Ini bukan hanya soal dua nama. Ini tentang wajah keadilan kita yang terus memudar, yang setiap hari menjadi cermin retak bagi jutaan orang yang tak punya privilese.
Kebenaran Formal: Legalitas yang Tak Serta-Merta Legitim
Secara konstitusional, Presiden berhak memberikan abolisi dan amnesti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan UU Darurat No. 11 Tahun 1954. Tapi seperti kata pepatah lama: “Tak semua yang legal itu bermoral, dan tak semua yang sah itu adil.”
Ketika Tom Lembong, yang sedang terjerat kasus kerugian negara karena izin impor gula senilai hampir Rp 200 miliar, dibebaskan dari proses hukum melalui abolisi; dan ketika Hasto Kristiyanto, yang sudah divonis dalam kasus obstruction of justice, mendapat amnesti yang membatalkan akibat hukum pidananya, maka sesungguhnya bangsa ini sedang membuat panggung politik baru, yaitu rekonsiliasi semu dan pengampunan selektif.
Alih-alih menjadi momen perbaikan sistem hukum, kedua keputusan ini menegaskan satu hal dimana hukum tidak berdiri di atas keadilan, melainkan tunduk pada konfigurasi kekuasaan.
Dimensi Ideologis, Hukum Siapa, Untuk Siapa?
Secara ideologis, abolisi dan amnesti ini tak bisa dibaca sebagai kebijakan biasa. Ia lahir dari sistem yang mewarisi dua penyakit akut demokrasi Indonesia yaitu elitisme hukum dan politik balas jasa.
1. Elitisme Hukum
Tak sedikit akademisi yang menyayangkan keputusan ini. Mereka mempertanyakan mengapa dua nama ini yang dipilih, di saat ribuan warga kecil mendekam dalam penjara karena kasus ringan seperti mencuri sendal, mengambil buah tetangga, atau tersandung kasus narkoba karena kemiskinan?
Dimanakah keadilan bagi Emak-emak di Karawang yang dihukum 3 bulan karena mencuri pakan ternak, atau bagi petani rempah di Maluku yang dikriminalisasi karena menolak tambang?
Ini adalah wajah sesungguhnya dari hukum kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika elite jatuh, hukum dibuat lentur. Ketika rakyat kecil terjerat, hukum berlaku sekeras baja.
2. Politik Balas Jasa
Amnesti dan abolisi ini juga punya jejak politik yang tak bisa diabaikan. Hasto adalah representasi kubu PDIP, partai besar yang saat ini menjadi oposisi, namun sinyal rekonsiliasi politik dengan pemerintah tercium dari banyak arah. Sedangkan Lembong adalah tokoh dari kubu Anies, rival kuat Prabowo di Pilpres.
Pemberian pengampunan kepada dua tokoh dari dua kutub politik ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar pertimbangan hukum, melainkan bagian dari strategi stabilisasi kekuasaan, menarik simpati dua kekuatan besar agar tak menjadi batu sandungan dalam masa transisi pemerintahan.
Konteks Historis, Abolisi dan Amnesti dalam Lintasan Waktu
Amnesti dan abolisi bukan hal baru di Indonesia. Kita pernah menyaksikan:
1. Amnesti 1960-an kepada pemberontak PRRI dan Permesta oleh Presiden Soekarno.
2. Amnesti dan abolisi 2005–2006 kepada mantan anggota GAM oleh Presiden SBY, sebagai bagian dari perjanjian damai Helsinki.
3. Amnesti 2017 oleh Jokowi untuk Saih Pining dan terpidana politik lainnya.
Namun semua itu berada dalam konteks rekonsiliasi besar, konflik bersenjata, atau krisis nasional. Sementara pemberian kepada Hasto dan Lembong jauh dari dimensi itu. Tak ada konflik sipil, tak ada pemberontakan. Yang ada hanyalah dua elite yang terjerat proses hukum.
Apakah ini berarti bahwa kita sedang menyamakan elite politik yang sedang diproses hukum dengan pejuang ideologis atau korban ketidakadilan struktural?
Wajah Ganda Keadilan, Ketika Rakyat Kecil Tak Punya “Presiden”
Mari kita bandingkan. Seorang warga desa mencuri ayam karena lapar. Ia diproses cepat, divonis tanpa pengacara, dan langsung ditahan. Ia tidak mendapat abolisi. Ia tidak punya partai. Ia bahkan tidak punya akun media sosial untuk menarik simpati publik.
Atau seorang aktivis lingkungan yang dihukum karena menolak proyek tambang di kampungnya. Ia tidak mendapat pembelaan di ruang publik. Bahkan tak disebut dalam sidang paripurna DPR. Tidak ada “surat pengampunan”.
Mereka semua menjalani hukum tanpa negosiasi, tanpa dispensasi, tanpa diskresi.
Di titik ini, keadilan bukan lagi prinsip universal, tapi menjadi produk relasi kuasa. Keadilan tidak dicapai melalui kesetaraan, tapi melalui koneksi dan kedekatan.
Ancaman Institusional, Kematian Perlahan Peradilan
Putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika bisa dibatalkan oleh kekuasaan eksekutif melalui keputusan politis. Ini bukan hanya soal Tom atau Hasto, tapi soal legitimasi institusi peradilan.
Apa arti proses penyidikan, pemeriksaan, dan persidangan jika pada akhirnya presiden bisa menganulir semua itu hanya dalam waktu sehari?
Apa artinya kemandirian hakim jika vonis mereka hanya menjadi “pengantar” sebelum abolisi turun?
Lembaga yudikatif sedang dikebiri secara simbolik. Dan ketika ini terjadi terus-menerus, publik tidak lagi percaya pada keadilan formal.
Apa yang Kita Wariskan kepada Generasi Selanjutnya?
Jika anak-anak muda hari ini menyaksikan bahwa elite yang bersalah bisa mendapat pengampunan, sementara rakyat kecil terus ditindas hukum, maka kita sedang mewariskan negara yang anti-meritokrasi, anti-keadilan, dan anti-konstitusionalitas.
Presiden boleh saja membuat kalkulasi politik, DPR bisa bersepakat atas nama rekonsiliasi, dan media bisa menulis narasi “penguatan hukum”. Tapi sejarah tidak lupa. Rakyat menyimpan memori. Dan memori tentang pengampunan bagi yang kuat dan kelupaan terhadap yang lemah akan menjadi luka panjang dalam perjalanan demokrasi kita.
Usul Ideologis, Jika Negara Serius pada Keadilan
Jika negara sungguh-sungguh ingin menunjukkan bahwa hukum tidak diskriminatif, maka berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh:
1. Bentuk Tim Amnesti Nasional untuk Rakyat Kecil, yang mengkaji ribuan kasus ringan yang dijalani rakyat miskin, lalu memberikan pengampunan kolektif dengan sistematik.
2. Transparansi dalam Pemberian Abolisi dan Amnesti, dengan keterlibatan publik, akademisi, dan masyarakat sipil, bukan hanya elite politik dan birokrat hukum.
3. Revisi UU tentang Abolisi dan Amnesti, agar pemberian pengampunan memiliki batasan moral, etis, dan prosedural yang ketat serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Lindungi Hakim dari Intervensi Kekuasaan, agar institusi peradilan tidak menjadi subordinat dari presiden, DPR, atau partai politik.
Saatnya Membangun “Negara Keadilan”, Bukan “Negara Kekuasaan”
Abolisi dan amnesti adalah alat yang sangat sakral. Ia bisa menjadi pengobat luka bangsa, bisa pula menjadi racun jika disalahgunakan.
Kita hidup di negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan karena itu, pengampunan kepada elite harus dipertanyakan, ditelaah, dan diawasi. Agar ke depan, hukum tidak hanya menjadi alat kuasa, tetapi sungguh menjadi rumah keadilan bagi semua.
Jika tidak, maka rakyat kecil hanya bisa berkata lirih: “Mengapa hukum hanya untuk kami, bukan untuk mereka?”
Wallahu’alam
Pondok Syarikat, 01 Agustus 2025
Sumber gambar: Wikipedia